Senin, 14 Juli 2025 23:32:46 WIB
Hegemoni yang Terdesak: Ketika Perang Dagang Justru Menguntungkan Tiongkok
Ekonomi
OPINI/Muhammad Rizal Rumra

Ilustrasi perang dagang AS-Tiongkok
Perang dagang yang diluncurkan Amerika Serikat (AS) terhadap Tiongkok sejak masa pemerintahan Donald Trump menjadi salah satu babak penting dalam sejarah ekonomi global kontemporer.
Langkah-langkah proteksionis, seperti pemberlakuan tarif tinggi terhadap produk-produk Tiongkok, pembatasan teknologi, serta kampanye internasional untuk mendiskreditkan perusahaan-perusahaan Tiongkok seperti Huawei dan TikTok, dimaksudkan untuk menekan pertumbuhan ekonomi dan membatasi pengaruh strategis negara tersebut.
Namun, data mutakhir tahun 2025 menunjukkan bahwa strategi ini tidak hanya gagal mencapai tujuannya, tetapi juga memunculkan dinamika baru dalam hubungan internasional dan sistem perdagangan global, yang justru menguntungkan Tiongkok.
Dari perspektif teori realisme struktural dalam hubungan internasional, negara-negara besar akan selalu berusaha memaksimalkan kekuatan mereka dan menekan pesaing yang tumbuh. AS melihat kebangkitan Tiongkok sebagai ancaman langsung terhadap hegemoninya, khususnya dalam ranah ekonomi dan teknologi.
Namun, asumsi realis bahwa tekanan ekonomi akan melemahkan lawan terbukti tidak berlaku sepenuhnya dalam kasus ini. Data terbaru dari Administrasi Umum Kepabeanan Tiongkok (GAC) menunjukkan bahwa pada paruh pertama tahun 2025, total impor dan ekspor barang Tiongkok naik menjadi 21,79 triliun yuan, meningkat 2,9 persen secara tahunan. Bahkan, ekspor Tiongkok melonjak 7,2 persen mencapai 13 triliun yuan, menjadi angka tertinggi sepanjang sejarah negara tersebut. Kenaikan ini menegaskan bahwa Tiongkok telah berhasil memitigasi dampak negatif dari tekanan ekonomi Amerika Serikat.
Fakta lain yang membantah efektivitas perang dagang adalah diversifikasi mitra dagang Tiongkok. Sebagaimana dilaporkan oleh GAC, lebih dari 51 persen perdagangan luar negeri Tiongkok pada paruh pertama 2025 berasal dari negara-negara yang tergabung dalam prakarsa Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative/BRI).
Perdagangan dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tumbuh 9,6 persen, dengan BRICS sebesar 3,9 persen, dan dengan Uni Eropa (UE) meningkat 3,5 persen. Berdasarkan perspektif neoliberalisme institusional, integrasi ekonomi melalui kerja sama multilateral dan perjanjian dagang memperkuat stabilitas sistem internasional.
Tiongkok telah memanfaatkan pendekatan ini dengan sangat efektif, membangun hubungan ekonomi yang erat dengan negara-negara di Asia Tenggara, Eurasia, Afrika, dan Amerika Latin. Hal ini menciptakan jaringan ketergantungan timbal balik (interdependensi kompleks) yang membuat upaya isolasi ekonomi oleh AS menjadi tidak efektif.
Salah satu pilar ketahanan ekonomi Tiongkok adalah sektor swasta yang kuat. Perusahaan-perusahaan swasta menyumbang 57,3 persen dari total perdagangan luar negeri pada paruh pertama 2025, dengan nilai perdagangan mencapai 12,48 triliun yuan yang naik 7,3 persen dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan sektor ini menunjukkan efektivitas model ekonomi "sosialisme dengan karakteristik Tiongkok" dalam menciptakan simbiosis antara kontrol negara dan dinamika pasar.
Dalam pandangan teori ekonomi politik internasional, khususnya mazhab developmental state, keberhasilan ini mencerminkan peran proaktif negara dalam mengarahkan pembangunan ekonomi tanpa harus tunduk pada prinsip-prinsip pasar bebas liberal Barat. Tiongkok memfasilitasi ekspor produk teknologi tinggi swasta yang naik 12,5 persen dan mendorong modernisasi industri manufakturnya, khususnya pada sektor kapal, otomotif, dan peralatan mesin.
Sementara itu, strategi de-coupling atau pemisahan ekonomi yang digagas oleh AS justru mempercepat terbentuknya kutub ekonomi baru. Buktinya, hubungan perdagangan Tiongkok dengan BRICS semakin erat. Nilai perdagangan dengan negara-negara BRICS mencapai 6,11 triliun yuan, mencakup 28 persen dari total perdagangan luar negeri Tiongkok. Kerja sama ini meliputi sektor strategis seperti industri petrokimia, logam, elektronik, pertanian, dan infrastruktur.
Dalam teori sistem dunia (world-systems theory), yang dikembangkan oleh Immanuel Wallerstein dapat dilihat bahwasanya Tiongkok sedang memosisikan dirinya sebagai inti (core) alternatif dari sistem ekonomi global, menantang dominasi AS yang selama ini menjadi inti tunggal dalam arsitektur kapitalisme global.
Meskipun data menunjukkan bahwa perdagangan Tiongkok dengan AS menurun tajam yakni 9,3 persen pada paruh pertama tahun 2025, hal ini tidak serta-merta melemahkan ekonomi Tiongkok. Sebaliknya, Tiongkok memanfaatkan momen ini untuk mengonsolidasikan integrasi ekonomi dengan kawasan Global South.
Di tengah tekanan tarif dan hambatan non-tarif yang diberlakukan oleh Washington, Tiongkok tetap mempertahankan daya saing ekspornya berkat kekuatan sistem industri domestik, kapasitas inovasi teknologi, serta jaringan rantai pasok global yang sudah sangat dalam. Penurunan perdagangan dengan AS justru menjadi katalis untuk mengurangi ketergantungan dan meningkatkan otonomi ekonomi strategis.
Pendekatan konstruktivis dalam hubungan internasional membantu menjelaskan mengapa narasi hegemonik AS kehilangan daya tarik di mata komunitas internasional. Tiongkok mengartikulasikan identitasnya sebagai mitra pembangunan global yang berkomitmen pada keterbukaan dan saling menguntungkan.
Inisiatif seperti pembangunan Pusat Keunggulan "Kepabeanan Cerdas" BRICS dan keterlibatan aktif dalam pembangunan infrastruktur negara-negara Selatan menunjukkan bahwa Tiongkok tidak hanya bermain dalam kerangka ekonomi semata, tetapi juga membentuk norma baru dalam tata kelola global. Ini kontras dengan pendekatan koersif dan unilateralis yang kerap diadopsi oleh AS, yang bagi banyak negara dianggap sebagai bentuk neoimperialisme ekonomi.
Di sisi lain, resistensi internal di AS terhadap perang dagang semakin menguat. Banyak perusahaan multinasional Amerika bergantung pada pasar dan pasokan dari Tiongkok, sehingga tekanan ekonomi dari pemerintah justru merugikan sektor bisnis domestik. Ketidakmampuan AS untuk memaksa reshoring (relokasi industri kembali ke Amerika) dalam skala besar menunjukkan bahwa integrasi ekonomi global telah melampaui batas kemampuan kontrol satu negara.
Bahkan menurut teori liberalisme ekonomi klasik, upaya memaksakan fragmentasi pasar bertentangan dengan logika efisiensi dan spesialisasi yang menjadi dasar perdagangan internasional modern.
Selain itu, data menunjukkan bahwa Tiongkok dan UE mencatat peningkatan perdagangan sebesar 3,5 persen pada paruh pertama tahun 2025. Dalam sektor teknologi hijau seperti generator tenaga angin dan transformator, Tiongkok menjadi eksportir utama ke Eropa.
Hal ini menandakan bahwa posisi Tiongkok sebagai pemain utama dalam transisi energi global semakin kokoh. Sementara itu, AS justru kehilangan momentum di bidang teknologi energi bersih karena fokus kebijakannya yang terpecah antara isolasionisme ekonomi dan persaingan geopolitik.
Di tengah ketegangan global, Tiongkok tetap konsisten dengan kebijakan "keterbukaan tingkat tinggi" dan pembangunan berkualitas, memperluas kerja sama strategis tidak hanya dengan negara maju tetapi juga negara berkembang.
Sebagaimana ditegaskan oleh Wakil Kepala GAC Wang Lingjun, Tiongkok menolak unilateralisme dan proteksionisme, serta mendorong dialog sebagai solusi konflik ekonomi. Hal ini memperkuat posisi moral dan diplomatik Tiongkok dalam arena global, sekaligus melemahkan legitimasi retorika Amerika yang mengaku sebagai pembela perdagangan bebas, padahal sering mempraktikkan proteksionisme selektif.
Penurunan perdagangan bilateral Tiongkok-AS sebesar hampir 10 persen memang nyata, tetapi justru membuka jalan bagi Tiongkok untuk melakukan reorientasi strategis perdagangan internasionalnya.
Dalam teori interdependensi kompleks yang dikemukakan oleh Robert Keohane dan Joseph Nye, aktor-aktor dalam sistem internasional tidak lagi hanya bertumpu pada kekuatan militer atau tekanan politik, melainkan pada jaringan ekonomi dan institusi global yang saling mengikat.
Dalam konteks ini, Tiongkok telah menavigasi struktur global secara cerdas, menggunakan kerja sama ekonomi sebagai instrumen diplomasi dan stabilisasi global. Itulah mengapa, perang dagang yang dilancarkan AS terhadap Tiongkok terbukti gagal secara strategis dan ekonomis. Alih-alih melemah, Tiongkok justru berhasil memperkuat struktur ekonominya, mendiversifikasi pasar, dan memperluas pengaruh globalnya.
Strategi tekanan unilateralis telah berbalik menjadi bumerang, memperlihatkan bahwa dalam era globalisasi baru yang multipolar, dominasi ekonomi tidak lagi dapat ditegakkan melalui koersif, tetapi harus dibangun melalui kerja sama, inovasi, dan kepercayaan. Dengan demikian, Tiongkok bukan hanya mampu bertahan dari tekanan AS, tetapi juga tampil sebagai kekuatan ekonomi dunia yang semakin tak tergoyahkan.
Komentar
Berita Lainnya
Banyaknya investasi yang masuk ke Jateng saat ini menjadi bukti bahwa Indonesia masih menjadi negara yang dipercaya para investor Ekonomi
Selasa, 4 Oktober 2022 18:8:39 WIB

Seperempat abad yang lalu Ekonomi
Kamis, 6 Oktober 2022 13:29:54 WIB

Selama liburan Hari Nasional tahun ini permintaan untuk perjalanan singkat dan penjualan peralatan luar ruangan terus meningkat Ekonomi
Jumat, 7 Oktober 2022 19:14:0 WIB

Shanghai mengharapkan mobil listrik penuh untuk membuat lebih dari setengah penjualan mobil pada tahun 2025 Ekonomi
Kamis, 13 Oktober 2022 21:21:32 WIB

Para petani cabai dan beras mengaku risau akan lonjakan harga akibat curah hujan yang tinggi sejak pekan lalu Ekonomi
Sabtu, 15 Oktober 2022 8:37:6 WIB

Huawei mengumumkan Ekonomi
Kamis, 20 Oktober 2022 10:1:4 WIB
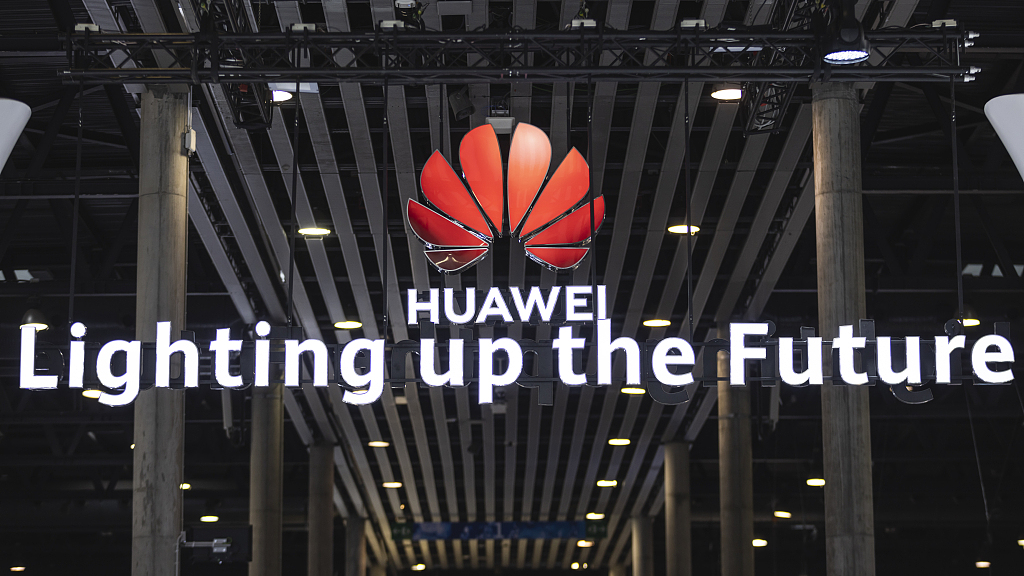
14 negara teken kesepakatan dagang dengan pengusaha Indonesia Ekonomi
Kamis, 20 Oktober 2022 15:36:8 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa di atas 5 Ekonomi
Sabtu, 22 Oktober 2022 11:45:9 WIB








