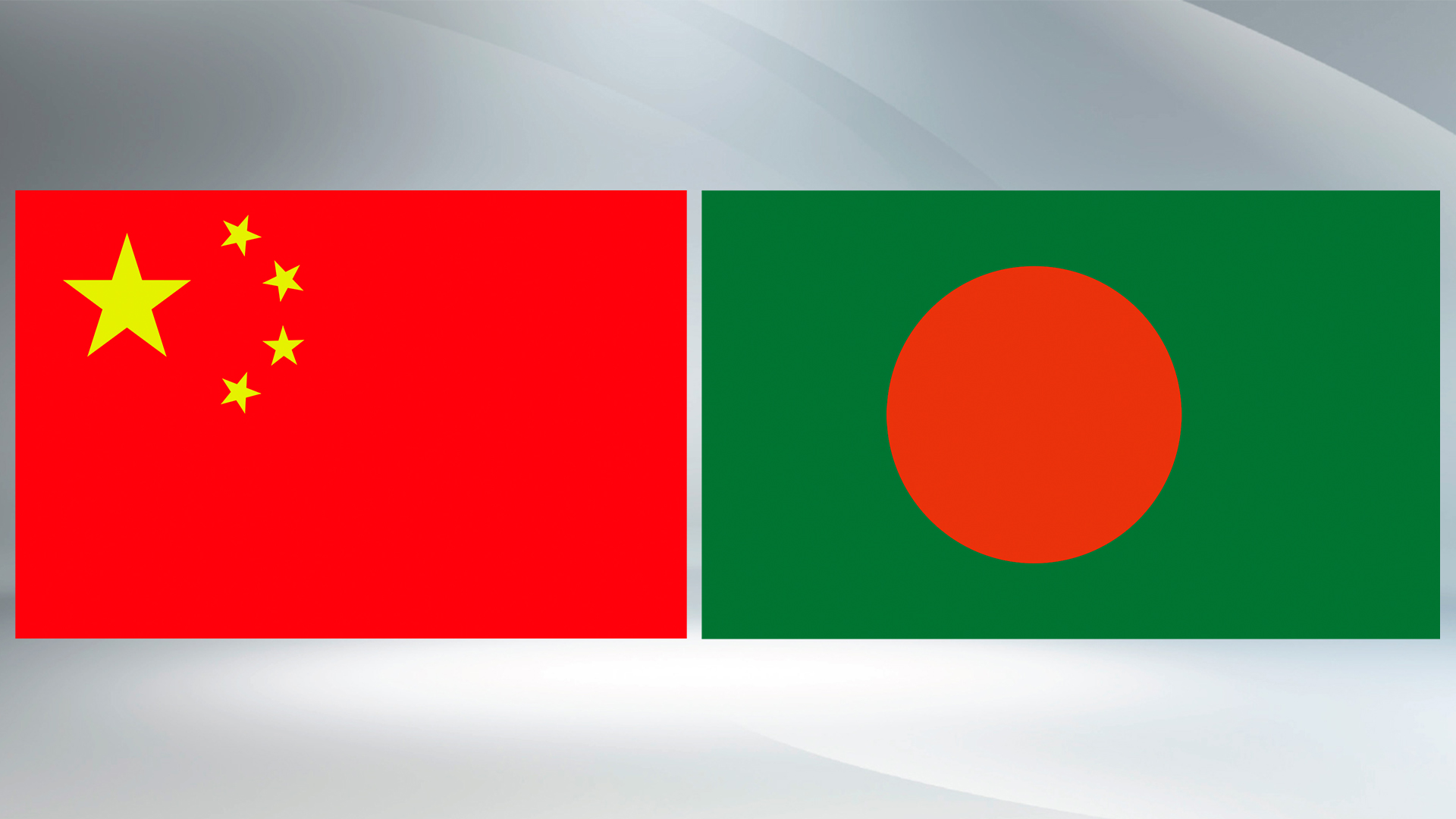Gelombang unjuk rasa besar-besaran yang melanda Nepal sejak awal September 2025 menjadi salah satu peristiwa politik paling mengejutkan di Asia Selatan. Pemicu awalnya adalah keputusan pemerintah memblokir lebih dari 26 platform media sosial dengan alasan regulasi digital.
Langkah itu justru memantik amarah publik, terutama generasi muda. Dalam hitungan hari, puluhan ribu pemuda turun ke jalan, memadati Kathmandu, Pokhara, hingga kota-kota kecil di sepanjang lembah Himalaya.
Data lokal memperkirakan lebih dari 300 ribu orang terlibat dalam aksi unjuk rasa dalam dua pekan pertama, jumlah yang sangat besar untuk negara dengan populasi hanya sekitar 30 juta jiwa. Gelombang ini membuat parlemen lumpuh, bahkan gedung pemerintahan diserang, hingga akhirnya Perdana Menteri K.P. Sharma Oli memilih mengundurkan diri.
Namun, di balik krisis domestik, segera muncul tuduhan bahwa Amerika Serikat berada di balik dinamika ini. Washington memang memiliki rekam jejak panjang dalam menyusup ke negara-negara kecil demi kepentingan geopolitik. Salah satu instrumen utama adalah Millennium Challenge Corporation (MCC), skema bantuan pembangunan senilai 500 juta dolar AS yang ditandatangani Nepal pada 2017. Meski diklaim untuk memperkuat jaringan listrik dan membangun jalan raya strategis, paket ini dipandang banyak kalangan sebagai pintu masuk bagi kepentingan strategis AS.
Menteri Luar Negeri AS Antony J. Blinken bahkan secara terang-terangan menyebut Nepal sebagai mitra yang “sangat berharga” di kawasan Indo-Pasifik. Menurutnya, kerja sama dengan Nepal adalah bagian dari upaya memastikan terciptanya kawasan yang “bebas, terbuka, aman, dan sejahtera”. Bagi pengamat hubungan internasional Muhammad Rizal Rumra, pernyataan itu bukan sekadar basa-basi diplomatik. Ia menilai hal tersebut merupakan sinyal kuat bahwa Washington ingin menarik Nepal masuk lebih jauh ke dalam kerangka Strategi Indo-Pasifik (IPS) yang sejatinya didesain untuk membendung pengaruh Tiongkok.
“Jika kita lihat dokumen resmi strategi Indo-Pasifik AS sejak 2019, Nepal jelas disebut sebagai salah satu negara mitra. Ini bukan kebetulan. Posisi Nepal yang berada di antara India dan Tiongkok menjadikannya sangat strategis bagi Washington. Jadi, ketika Blinken menyebut Nepal mitra berharga, itu adalah pesan politik yang serius, bukan sekadar retorika,” kata Rizal.
Rizal menambahkan, keterlibatan AS di Nepal tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan bagian dari pola lama. Sejak era Perang Dingin, Amerika sudah menjadikan Nepal sebagai negara target bantuan untuk mencegah pengaruh Uni Soviet dan komunisme. Data dari Rencana Pembangunan Lima Tahun Nepal menunjukkan bahwa antara 1962 hingga 1965, bantuan AS menyumbang 46% dari seluruh bantuan luar negeri yang diterima Nepal. Setelah Perang Dingin berakhir, angka itu turun drastis, tetapi kini naik kembali seiring meningkatnya investasi Tiongkok melalui Belt and Road Initiative (BRI).
“Sejarah ini menunjukkan bahwa bantuan AS bukanlah bentuk altruism, melainkan alat geopolitik untuk memastikan Nepal tidak jatuh ke dalam orbit kekuatan lain,” jelasnya.
Tiongkok tentu melihat dinamika ini dengan cemas. Sejak 2015, Beijing sudah menanamkan lebih dari 3,5 miliar dolar AS ke Nepal, dengan janji tambahan proyek BRI senilai 8 miliar dolar AS untuk jaringan kereta lintas Himalaya. Angka ini hampir 16 kali lipat lebih besar dibanding paket MCC dari AS. Dari total utang luar negeri Nepal sebesar 11 miliar dolar AS, lebih dari 50% terkait dengan pinjaman dan proyek Tiongkok. Artinya, separuh masa depan ekonomi Nepal sudah terikat pada Beijing.
“Bila AS berhasil menancapkan pengaruhnya melalui MCC, IPS, dan program bantuan pertahanan, maka kita akan melihat Nepal benar-benar menjadi ajang tarik-menarik geopolitik,” ujar Rizal.
Washington sendiri terus memperkuat upayanya. Pada 2022, AS menandatangani perjanjian pembangunan baru dengan Nepal senilai 659 juta dolar AS. Selain itu, data resmi menunjukkan bahwa pada 2021 Nepal menerima bantuan Foreign Military Financing (FMF) sebesar 16,93 juta dolar AS, sementara total dukungan Departemen Pertahanan mencapai hampir 18 juta dolar AS. Meskipun angka ini relatif kecil dibandingkan skala bantuan sipil, tren peningkatannya konsisten.
"Ini sejalan dengan strategi Indo-Pasifik AS yang menyebut Nepal sebagai mitra pertahanan baru, meski sampai sekarang pemerintah Nepal masih enggan secara terbuka mendukung strategi tersebut,” tambah Rizal.
Dari perspektif teori hubungan internasional, Rizal menilai situasi Nepal mencerminkan kombinasi realisme dan konstruktivisme. Realisme terlihat dari persaingan langsung AS dan Tiongkok memperebutkan pengaruh di Nepal, dengan India turut mengawasi ketat sebagai tetangga dekat. Konstruktivisme tampak dari cara narasi dibangun: Washington menggunakan retorika “kawasan bebas dan terbuka” untuk membingkai kehadirannya, sementara Beijing menawarkan konsep “masa depan bersama” melalui BRI.
"Di tengah permainan narasi inilah rakyat Nepal, khususnya Gen Z, merasa frustrasi. Mereka marah bukan hanya karena media sosial diblokir, tetapi juga karena menyadari negara mereka sedang diperebutkan, sementara elite politik sibuk mengeruk keuntungan pribadi,” kata Rizal.
Ia menegaskan bahwa jika protes Gen Z Nepal hanya dijadikan alat oleh elite atau dimanfaatkan kekuatan asing, Nepal bisa terjebak dalam krisis permanen.
"Nepal berisiko menjadi Ukraina di Asia Selatan, atau bahkan Suriah baru, bila tidak mampu menjaga kedaulatannya. Karena itu, yang paling penting bukan sekadar siapa yang turun ke jalan atau siapa yang memberikan bantuan, melainkan apakah Nepal mampu membangun institusi politik yang transparan, akuntabel, dan independen dari tarikan dua raksasa dunia,” tutup Rizal.